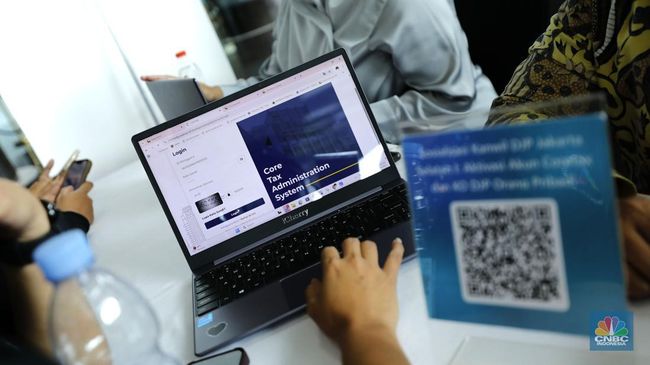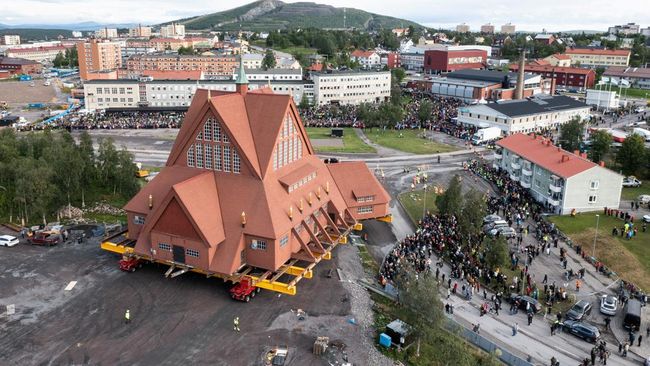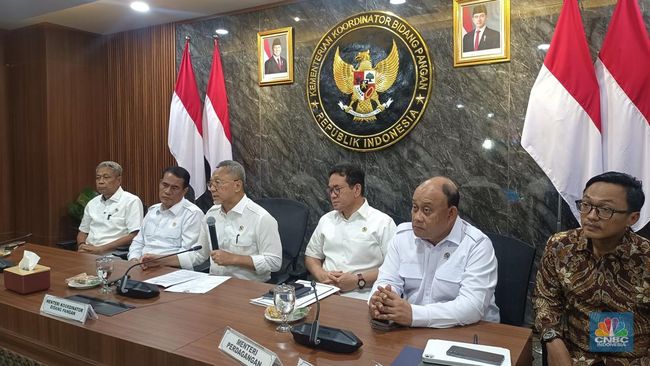Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Pada pertengahan tahun 1930an, Joseph Schumpeter memiliki mahasiswa kesayangan di program studi doktoral ilmu ekonomi Harvard. Mahasiswa tersebut terbilang sangat cerdas, setidaknya dalam pandangan Schumpeter. Namanya Paul Sweezy. Pun Schumpeter, yang saat itu sudah menjadi profesor di Harvard, menjadi pembimbing langsung disertasi Sweezy, sekaligus sebagai salah satu guru Sweezy yang paling berpengaruh.
Hal itu terbukti dari buku pertama Paul Sweezy yang diadopsi dari desertasinya. Buku berjudul "Monetary Theory and Capitalist Development (1938) karya Sweezy sangat kental pengaruh pemikiran Schumpeter, meskipun Sweezy sudah cukup terpapar pemikiran kiri kala itu.
Buku pertama Sweezy tersebut masih terbilang kurang "Marxian", walaupun nuansa-nuansa ke arah sana tetap ada. Tapi nuansa itu tidak hanya lahir karena tendensi Sweezy yang kiri, tapi juga dari pengaruh Schumpeter yang memang memiliki pemikiran unik di dalam kajian ekonomi.
Schumpeter secara kategoris masih tergolong ke dalam penganut teori ekonomi liberal konservatif. Tapi perbedaan Schumpeter dengan ekonom-ekonom liberal konservatif lainya adalah bahwa Schumpeter sangat mengistimewakan Karl Marx.
Dalam bukunya "Capitalism, Socialism, and Democracy" (1942), misalnya, ia menyebut Karl Marx sebagai "the greatest of all economists." Bahkan pada buku awalnya, "The Theory of Economic Development" (1911), dari bab satu sampai empat, Schumpeter tak pernah ketinggalan memasukkan pemikiran Karl Marx ke dalam empat bab tersebut.
Pandangan semacam ini akhirnya membuat Schumpeter cukup terbuka ketika membimbing Sweezy yang sudah cukup terpengaruh oleh pemikiran Marx. Perbedaan keduanya, Schumpeter melihat kapitalisme akan hancur oleh kesuksesannya sendiri (seperti karena monopoli korporasi besar misalnya).
Sementara Sweezy menekankan kontradiksi internal yang membuat krisis tak terelakkan dari sistem kapitalisme, sama dengan pandangan Karl Marx. Kelebihan Sweezy dari Marx adalah bahwa Sweezy memberikan landasan pemikiran yang lebih ilmiah dan metodologis atas pemikiran-pemikiran Karl Marx.
Dengan latar yang demikian, tak pelak, ekonom muda brilian tersebut digadang-gadang akan menjadi penerus nama besar Joseph Schumpeter di Harvard. Pun dari banyak sumber dikatakan bahwa Joseph Schumpeter sendiri sangat berharap Paul Sweezy akan meneruskan segala warisan pemikiran Schumpeter bersama dengan Harvard University. Tapi tak dinyana, harapan tersebut buyar tak lama setelah Sweezy menyelesaikan studi doktoralnya.
Ketika buku kedua Sweezy terbit, "The Theory of Capitalist Development" (1942), ternyata buku tersebut sekaligus menjadi pemisah permanen antara Sweezy dan gurunya. Buku kedua Sweezy tersebut menjadi titik sentral pergeseran total Sweezy ke jalur Marxisme. Melalui buku kedua itu, Sweezy berusaha menyusun ulang teori Karl Marx dalam kerangka yang lebih sistematis, logis, dan dapat dipahami oleh generasi baru Amerika di masa itu.
Diakui oleh banyak pihak bahwa karya ini menjadi salah satu tonggak penting dalam pengembangan ekonomi politik Marxian, khususnya di Amerika Serikat, dan kerap dijadikan rujukan bagi para akademisi maupun aktivis yang ingin memahami logika perkembangan kapitalisme dari kacamata sosialisme.
Menurut Sweezy, kapitalisme bukanlah sistem ekonomi yang netral, melainkan sistem yang memiliki kontradiksi internal berkelanjutan. Akumulasi kapital, yang menjadi jantung dari perkembangan kapitalisme, pada akhirnya menghasilkan ketegangan antara produktivitas yang meningkat di satu sisi dan keterbatasan konsumsi massa di sisi lain. Dan hal itu, menurut Sweezy, akan menyebabkan tendensi stagnasi dan krisis berkala di dalam sistem kapitalisme di mana pun sistem itu diterapkan.
Lebih jauh lagi, Sweezy juga membuat teori nilai kerja Marx menjadi lebih jelas dan komprehensif. Ia menekankan bahwa nilai suatu komoditas ditentukan oleh "waktu kerja sosial yang diperlukan" untuk memproduksinya. Dari sinilah muncul konsep nilai lebih (surplus value) yang dihasilkan oleh buruh tetapi diambil oleh kapitalis. Dan menurut Sweezy, inilah sumber utama eksploitasi dalam kapitalisme, dan akar dari ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi.
Sweezy menekankan perbedaan mendasar antara produksi untuk keuntungan (profit) dan produksi untuk kebutuhan (use). Kapitalisme, menurutnya, selalu menempatkan keuntungan di atas kebutuhan manusia alias mengutamakan kerakusan. Hal inilah yang membuat sistem kapitalisme tidak hanya eksploitatif, tetapi juga tidak rasional dari sudut pandang sosial.
Dan tak lupa, Sweezy juga dikenal karena pandangannya yang tajam tentang imperialisme. Ia melihat ekspansi ke luar negeri sebagai cara kapitalisme mencari pasar baru, sumber bahan mentah, dan peluang investasi ketika pasar domestik semakin jenuh. Pandangan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam karyanya bersama Paul Baran berjudul "Monopoly Capital", di mana benih-benih awal dari isi buku tersebut sebenarnya sudah ada dalam The Theory of Capitalist Development.
Pergeseran Paul Sweezy ke "kiri jauh" (far left) membuatnya harus menerima sanksi dari Harvard, yakni dikeluarkan. Atas nama membela pemikiran bebas dan sosialisme, Sweezy menerima sanksi tersebut dengan senang hati.
Akibat sanksi dari Harvard, Sweezy akhirnya dekat dengan beberapa orang penting yang sangat berarti di dalam perjalanan intelektualnya. Misalnya pada 1948, Sweezy bertemu kembali dengan Leo Huberman, seorang penulis dan intelektual kiri yang juga prihatin dengan situasi intelektual Amerika saat itu.
Berkat pertemuan kembali tersebut, keduanya sepakat mendirikan sebuah jurnal bulanan yang bisa menjadi wadah analisis ekonomi-politik radikal sekaligus bacaan populer bagi kalangan progresif. Inilah awal cerita dari lahirnya Jurnal Monthly Review, yang sampai hari ini masih eksis. Dana awal Monthly Review datang dari Francis Otto Matthiessen, seorang profesor sastra terkenal di Harvard, yang juga dikenal sebagai intelektual kiri dan penyokong gerakan progresif.
Matthiessen memberikan dana hibah pribadi sebesar USD 5.000 (jumlah yang besar untuk saat itu) kepada Sweezy dan Huberman agar jurnal bisa berjalan. Dukungan ini memungkinkan penerbitan edisi perdana pada Mei 1949.
Tokoh penting dan "besar" lainya yang dekat dengan Sweezy adalah Albert Einstein. Hubungan keduanya cukup menarik, karena merupakan pertemuan dua tokoh besar dari bidang yang berbeda, seorang ekonom Marxian dengan seorang fisikawan revolusioner, namun memiliki keprihatinan yang sama terhadap masalah sosial dan politik dunia.
Pada tahun 1930-an hingga 1940-an, Paul Sweezy sudah dikenal sebagai ekonom muda yang kritis terhadap kapitalisme. Sementara itu, Albert Einstein, yang sudah menjadi figur dunia berkat teori relativitasnya, semakin aktif menyuarakan pandangan sosial dan politik, khususnya setelah ia bermigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1933 karena ancaman Nazi di Jerman. Tak pelak, pertemuan mereka berubah menjadi pertemanan yang "klop".
Tak banyak yang mengetahui, Albert Einstein menulis satu artikel untuk edisi perdana jurnal "Monthly Review", yang diakui oleh banyak pihak, berhasil memberikan legitimasi moral kepada jurnal tersebut sampai hari ini. Einstein menulis esai terkenal berjudul "Why Socialism?" (1949) di jurnal Monthly Review edisi perdana.
Einstein membuka tulisannya dengan menggambarkan kondisi manusia modern yang terjebak dalam keterasingan (alienation, istilah yang sangat tenar di dalam kajian Marxisme tentunya). Menurutnya, manusia merasa kecil, tak berdaya, dan terisolasi dalam masyarakat yang semakin kompleks. Ia menilai bahwa kapitalisme melahirkan kompetisi yang brutal dan merusak solidaritas sosial.
Selain itu, kapitalisme, kata Einstein, menyebabkan ketidakadilan yang sistematis dalam distribusi kekayaan. Segelintir orang menguasai alat-alat produksi, sementara mayoritas bekerja hanya untuk bertahan hidup. Akibatnya, jurang antara kaya dan miskin semakin melebar, dan kesempatan hidup layak bagi banyak orang semakin terbatas.
Einstein menyoroti bagaimana pendidikan dalam masyarakat kapitalis seringkali diarahkan untuk melayani kepentingan kelas berkuasa. Alih-alih membentuk individu yang bebas dan kreatif, sistem pendidikan cenderung menyiapkan tenaga kerja yang patuh pada logika pasar. Menurutnya, hal ini membatasi perkembangan potensi manusia.
Tak lupa, Einstein juga menekankan bahwa manusia sejatinya adalah makhluk sosial. Kehidupan manusia hanya bermakna dalam hubungan dengan sesamanya. Sementara, kapitalisme justru mendorong individualisme sempit, yang menghancurkan nilai kebersamaan dan solidaritas.
Sehingga dalam konteks inilah Einstein menawarkan sosialisme sebagai alternatif. Baginya, sosialisme bukan sekadar sistem ekonomi, melainkan upaya membangun masyarakat yang berlandaskan solidaritas, kerja sama, dan keadilan sosial.
Sosialisme, menurutnya, harus menjamin kebutuhan dasar setiap orang, menghapus ketidakadilan distribusi, serta mencegah kekuasaan politik dikuasai oleh minoritas kaya. Salah satu kutipan terbaik di dalam artikel Einstein tersebut, setidaknya menurut saya, adalah "The economic anarchy of capitalist society as it exists today is, in my opinion, the real source of the evil." (Anarki ekonomi masyarakat kapitalis saat ini adalah, menurut saya, sumber utama dari segala keburukan.)
Lantas apa hubungan cerita ini terhadap Prabowo? Dalam hemat saya, yang disebut oleh Prabowo sebagai serakahnomic, tak berbeda dengan semua kritik yang diberikan oleh Paul Sweezy dan Einstein atas kapitalisme.
Pembedanya adalah konteks. Konteks Sweezy dan Einstein adalah kapitalisme pada umumnya. Sementara konteks Prabowo adalah konteks kapitalisme Indonesia. Namun poin-poin "serangannya" kepada kapitalisme sejatinya sama saja, kerakusan pemilik modal dan imbas ketidakadilan yang disebabkanya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan istilah serakahnomics (tentunya berasal dari kombinasi kata "serakah" dan "economics") sebagai kritik tajam terhadap praktik ekonomi tidak etis yang hanya memikirkan profit tanpa memperhatikan rakyat. Menurutnya, ini bukan lagi bagian dari mazhab ekonomi mapan seperti liberal, pasar bebas, atau sosialis, melainkan "ilmu serakah" yang merusak moral dan melanggar hukum serta konstitusi.
Prabowo menggambarkan para pelaku serakahnomics sebagai "vampir ekonomi" atau "parasit" yang menghisap kekayaan bangsa dan memperkaya diri di atas penderitaan masyarakat. Ia menyoroti praktik kriminal seperti pengoplosan beras subsidi menjadi "beras premium" hingga distribusi pangan strategis yang dimanipulasi demi keuntungan besar, menyebabkan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 100 triliun per tahun.
Pandangan kritis Prabowo tentang gurita kapital yang merugikan kehidupan sosial masyarakat banyak pun sebenarnya bukanlah hal baru. Sebut saja misalnya pandangan Bung Hatta tentang keadilan ekonomi. Konsep keadilan ekonomi menurut Bung Hatta berakar pada semangat kolektivitas dan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata pada akumulasi kapital.
Bagi Hatta, pembangunan ekonomi harus berorientasi pada manusia dan kebutuhannya, bukan pada segelintir pemodal. Ia menegaskan bahwa ekonomi Indonesia idealnya berdiri di atas asas kekeluargaan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 yang turut ia rumuskan. Karena itulah dalam pandangan Hatta, koperasi adalah wujud paling nyata dari demokrasi ekonomi.
Bung Karno memandang keadilan ekonomi sebagai syarat mutlak bagi terwujudnya masyarakat adil dan makmur, di mana kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan ekonomi hanyalah kemerdekaan semu. Ia menolak sistem kapitalisme yang menindas serta kolonialisme ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir orang, dan menekankan pentingnya ekonomi gotong royong sebagai jalan keluar.
Dalam salah satu pidatonya, Soekarno menegaskan, "Politik tidak lain hanyalah alat. Tujuan kita ialah masyarakat adil dan makmur, dengan beresnya soal perut rakyat, beresnya soal sandang, pangan, dan papan."
Bahkan hampir semua tokoh pendiri bangsa ini, jika kita dalami satu persatu isi kepala mereka, akan muncul substansi pandangan yang sama di mana keadilan ekonomi adalah kunci di dalam pengelolaan ekonomi nasional setelah Indonesia merdeka. Mengapa? Karena memang luka dari kolonialisme dan imprealisme selama ratusan tahun sangatlah menyakitkan.
Namun lagi-lagi masalahnya bukanlah pada tataran teori, narasi, atau retorika tentang keadilan ekonomi, tapi terletak pada praktek nyata dari kekuasaan negara di dalam mewujudkannya. Sejarah telah mengajarkan bahwa narasi-narasi ideal dan manis biasanya cenderung tergelincir di dalam praktiknya karena berbagai faktor.
Masalahnya, karena cerita masa lalu yang kurang "mulus" dengan kelompok kiri, kata sosialisme ikut tenggelam di Indonesia, meskipun secara ekonomi sebenarnya pasal-pasal tentang pengelolaan kekayaan negara dituliskan di dalam logika sosialis, bukan kapitalis.
Dan masalah lainnya adalah bahwa pasal-pasal tersebut di dalam prakteknya nyaris tak berbunyi. Nampaknya, karena itulah Prabowo menggunakan istilah "serakahnomics" untuk menyerang kapitalisme tersebut, bukan dengan memperkenalnya konsep "sosialisme pasal 33 UUD 1945". Prabowo menyerang kapitalisme dengan cara "negative labelling" terhadap praktek-praktek buruk kapitalisme Indonesia.
Padahal, kalau mau jujur, solusi strategis yang ditawarkan Prabowo sebenarnya tak berbeda dengan solusi-solusi sosialis. Hanya saja, untuk menyebut satu kata tersebut nampaknya memang tak mudah, sekalipun kritik Prabowo sama saja dengan poin-poin kritik Albert Einstein di dalam artikel "Why Socialism?"-nya.
Di era Orde Baru, istilah penggantinya adalah ekonomi Pancasila, di mana poin-poinnya sejatinya juga tak jauh berbeda berbagai kritik yang dilontarkan oleh Sweezy dan Albert Einstein atas kapitalisme.
Berbeda dengan China, misalnya, untuk membedakan praktek ekonomi China dengan sistem kapitalisme di satu sisi dan Maoisme di sisi lain, China sampai hari ini masih percaya diri menggunakan istilah "sosialisme berkarakteristik China (socialism with China's characteristic)" di mana praktek kapitalisme di lakukan di bawah kendali negara, tapi praktek sosialisme juga tetap dijalankan dengan penampakan yang toleran kepada kapitalisme.
Terlepas dari perbedaan istilah tersebut, lagi-lagi persoalannya sebenarnya ada pada praktek. Indonesia dalam sejarahnya memang bermasalah dengan praktek. Sukarno sendiri meninggalkan kekuasaan di dalam kondisi ekonomi negara yang begitu sulit, setelah berapi-api melawan kapitalisme - imprealisme. Bayangkan saat itu, negara saja hampir kolaps secara ekonomi, apalagi saku dan perut rakyat Indonesia.
Suharto yang merasakan bahwa kondisi tersebut harus dirubah akhirnya membawakan narasi yang agak berbeda , namun dengan substansi yang sama, yakni keadilan ekonomi dengan platform ekonomi Pancasila, di mana secara ideologis Indonesia semestinya memilih jalan tengah.
Tidak ke kiri pun tidak ke kanan. Tidak kapitalistik, tidak pula sosialistik-komunis. Tapi Pancasilais. Sayangnya, dalam perjalanan Suharto pun meninggalkan panggung kekuasaan dalam kondisi ekonomi negara yang juga hampir "tepar" dan "pingsan", bahkan kurang "Pancasilais" malah.
Era reformasi berusaha mengoreksinya. Praktek-praktek rakus dan serakah pelaku ekonomi yang sudah terlanjur mengalami "kawin-mawin" dengan kekuasaan diharapkan dikoreksi secara substantif pasca-Orde Baru selesai. Namun yang terjadi juga tak seindah teori para aktor reformis 1998.
Kekuasaan ekonomi yang semula berada di dalam jejaring "sultanic oligarchy" Orde Baru, meminjam istilah dari Professor Jeffrey Winter, menyebar ke banyak pusat kuasa baru, lalu semakin membesar secara berkelanjutan selama 25 tahun lebih era Reformasi.
Jejaring kerakusan dan keserakahan menyebar ke mana-mana, berkolusi dengan banyak pusat-pusat kuasa baru, dan menciptakan kelas "1 persen" nasional yang semakin "rakus" terhadap sumber daya ekonomi Indonesia. Dan secara kategorial, Prabowo dan keluarganya ada di dalam golongan satu persen ini.
Karena faktor tabu tersebut, tentu menjadi agak kurang relevan jika pertanyaanya kemudian terkait dengan keberanian Prabowo di dalam menyuarakan "sosialisme berkarakter Indonesia" memakai referensi Paul Sweezy dan Albert Ensitein.
Pertanyaan yang tepat, dalam hemat saya, adalah Apakah Prabowo mampu menjadi seorang Franklin Delano Roosevelt, yang dianggap oleh H.W. Brand sebagai "pengkhianat terhadap kelasnya" (judul bukunya: Traitor to His Class: The Privileged Life and Radical Presidency of FDR, 2009).
Meski berasal dari keluarga aristokrat dan kaya, FDR dianggap mampu mengubah arah ekonomi Amerika dari kanan ke sayap agak kiri dengan hasil yang cukup menuai banyak pujian di kubu liberal (demokrat) sekaligus gunjingan negatif dari kubu konservatif.
Legasi ekonomi FDR bertahan di Amerika sampai tahun 1960an akhir, sebelum Amerika dihajar krisis "Great Inflation", meminjam istilah dari Robert J. Samuelson , dalam bukunya "The Great Inflation and Its Aftermath: The Past and Future of American Affluence (2008).
Pendeknya di sini saya ingin mengatakan bahwa perkaranya bukanlah pada istilah baru untuk masalah lama yang sudah ada di negeri ini sejak dulu. Sekalipun serakahnomic mendadak tenar sebagai bentuk kritik terbuka Prabowo kepada praktek kapitalisme rakus ala Indonesia, kuncinya tetap ada para praktek dan realisasi.
Pertama, apa rencana strategis dari platform Prabowonomics di dalam menyelesaikan masalah "serakahnomic" tersebut? Kedua, karena lagunya adalah lagu lama yang dikemas dengan istilah kekinian, di mana hampir persis sama dengan konsep-konsep ideal Orde baru, apa strategi dan rencana manajemen risiko dari Prabowonomics agar Indonesia tidak tercebur ke lubang yang sama pada akhirnya?
Lubang yang sama adalah "moral hazard" yang terjadi di tengah jalan akibat menggumpalnya kekuasaan ekonomi di tangan segelintir pihak yang dipercaya oleh Prabowo, termasuk segelintir pihak yang dihadirkan secara institusional, lalu pada ujungnya menyebabkan pembusukan pada substansi-substansi manis yang sempat dihadirkan oleh platform Prabowonomics.
Pasalnya, penumpukan kekuasaan dan sumber daya di tangan negara, beserta jejaring koalisi ekonomi politiknya yang "tambun", memiliki risiko yang tak jauh berbeda dengan penumpukan kuasa ekonomi secara berlebihan di tangan pelaku pasar.
Sehingga dibutuhkan "blueprint" preventif-antisipatif yang benar-benar jelas sekaligus teruji, baik secara historis maupun secara komparatif, agar Prabowonomics sebagai antitesis dari Serakahnomics tidak berujung "nomics-nomics" lain yang juga buruk bagi negeri ini di kemudian hari.
Jika Prabowo bisa membuktikan bahwa pemerintahannya bisa memberantas serakahnomics dan menjalankan ekonomi Pancasila dengan lurus dan konsisten, pada saat itulah sebenarnya Prabowo sedang mempraktikan "Sosialisme dengan karakter Indonesia"
(miq/miq)