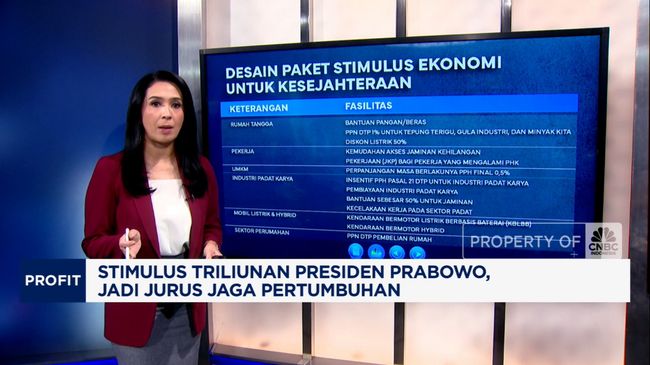Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang efektif berlaku pada 24 Februari 2025 memunculkan satu ketentuan penting yang secara mendasar merekonstruksi paradigma hukum terhadap status hukum pengelola BUMN.
Dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, terdapat dua pasal penting yang menjadi tantangan KPK, yaitu: Pasal 3X Ayat (1) berbunyi "Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara". Pasal 9G berbunyi "Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara".
Ketentuan ini, meskipun terkesan teknokratis, memiliki implikasi hukum yang sangat besar terhadap rezim pertanggungjawaban pidana para pengelola BUMN.
Selama ini, berbagai praktik penegakan hukum kerap kali menempatkan direksi dan komisaris BUMN sebagai subjek utama dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor), terutama jika BUMN mengalami kerugian atau kegagalan investasi. Padahal, kerugian dalam konteks dunia usaha tidak serta merta menjadi dasar adanya unsur perbuatan melawan hukum, apalagi tindak pidana.
Prinsip Business Judgment Rule (BJR) merupakan salah satu doktrin penting dalam hukum korporasi yang memberikan batasan terhadap kemungkinan pertanggungjawaban direksi atau komisaris atas keputusan bisnis yang mereka ambil.
Secara umum, BJR adalah asas yang menyatakan bahwa pengadilan tidak seharusnya mencampuri atau mengadili substansi keputusan bisnis yang dibuat oleh direksi atau komisaris, selama keputusan tersebut dibuat secara wajar, dengan iktikad baik, tanpa benturan kepentingan, dan berdasarkan informasi yang memadai.
Prinsip tersebut memberikan pengakuan terhadap sifat dinamis dan penuh risiko dari pengambilan keputusan dalam dunia bisnis, yang pada kenyataannya tidak selalu berujung pada keberhasilan atau keuntungan.
Rasio legis dari prinsip ini terletak pada perlindungan terhadap independensi dan profesionalitas manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis. Tanpa adanya prinsip seperti BJR, maka setiap kerugian atau kegagalan yang terjadi dalam aktivitas usaha bisa dengan mudah dijadikan dasar untuk menjerat direksi atau komisaris dengan tanggung jawab hukum, termasuk pidana.
Hal itu akan menciptakan iklim manajerial yang defensif, di mana pengambil keputusan menjadi enggan mengambil risiko, padahal keberanian mengambil risiko yang terukur adalah esensi dari inovasi dan pertumbuhan usaha. Maka dari itu, BJR bertujuan untuk mendorong manajemen agar tetap proaktif dan tidak takut gagal, selama proses pengambilan keputusan telah mengikuti standar kehati-hatian yang wajar secara korporatif.
Dalam doktrin hukum korporasi, terutama yang berkembang dalam sistem common law seperti di Amerika Serikat, BJR telah diterima sebagai prinsip yang membatasi ruang campur tangan pengadilan terhadap pertimbangan bisnis.
Doktrin itu kemudian diadopsi dalam berbagai sistem hukum lain, termasuk Indonesia, yang secara eksplisit mengakui prinsip serupa melalui Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal tersebut menegaskan bahwa direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan bahwa pengurusan dilakukan dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan untuk kepentingan terbaik perseroan.
BJR lahir dari pemahaman bahwa dunia usaha adalah ranah yang penuh risiko. Maka, apabila setiap kerugian BUMN dikriminalisasi tanpa menguji proses pengambilan keputusannya, hal ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip korporasi modern, tetapi juga merusak semangat profesionalisme dan manajerial yang seharusnya menjadi tulang punggung BUMN.
Dengan UU BUMN 2025 secara eksplisit mengeluarkan direksi dan komisaris dari kategori "Penyelenggara Negara", maka tidak lagi relevan untuk menerapkan UU Tipikor secara langsung kepada pengurus BUMN kecuali ditemukan adanya niat jahat (mens rea) dan keuntungan pribadi yang tidak sah.
Namun, agar prinsip ini bisa berjalan secara konsisten dan utuh, perlu dilakukan pembaruan kebijakan keuangan negara terhadap BUMN. Salah satu kelemahan utama selama ini adalah masih kuatnya keterlibatan fiskal negara melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), bahkan kepada BUMN yang secara ekonomi sudah tidak viable.
Selama negara masih rutin menyuntikkan dana kepada BUMN yang merugi, maka akan selalu terbuka peluang pengawasan ekstra ketat dari lembaga penegak hukum, termasuk KPK, karena dana tersebut berasal dari APBN. Di sinilah celah penarikan BUMN ke dalam rezim "pengelolaan keuangan negara" kembali terbuka, meski secara hukum korporasi, BUMN adalah badan hukum privat.
Maka, untuk mewujudkan prinsip BUMN sebagai korporasi yang mandiri dan profesional, pemerintah harus menghentikan PMN kepada BUMN yang tidak memiliki prospek usaha yang jelas, dan mendorong skema pembiayaan alternatif seperti pasar modal, obligasi korporasi, atau strategic partnership.
UU BUMN 2025 memberikan peluang besar untuk membangun ekosistem korporasi negara yang rasional, profesional, dan bebas intervensi politik dan kriminalisasi hukum. Namun, untuk mewujudkannya, dibutuhkan komitmen konsisten dalam menerapkan BJR dan memutus ketergantungan fiskal BUMN kepada negara. Karena hanya dengan demikian, BUMN dapat menjadi agen pembangunan yang mandiri dan kompetitif di tengah era globalisasi ekonomi.
(miq/miq)