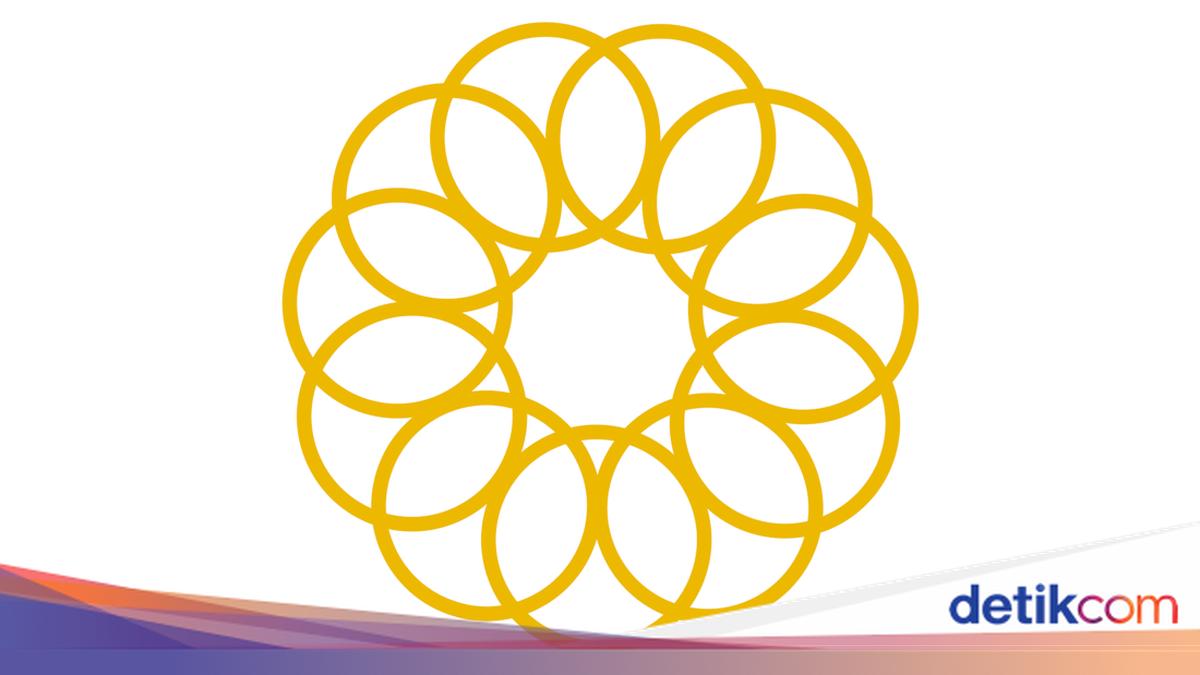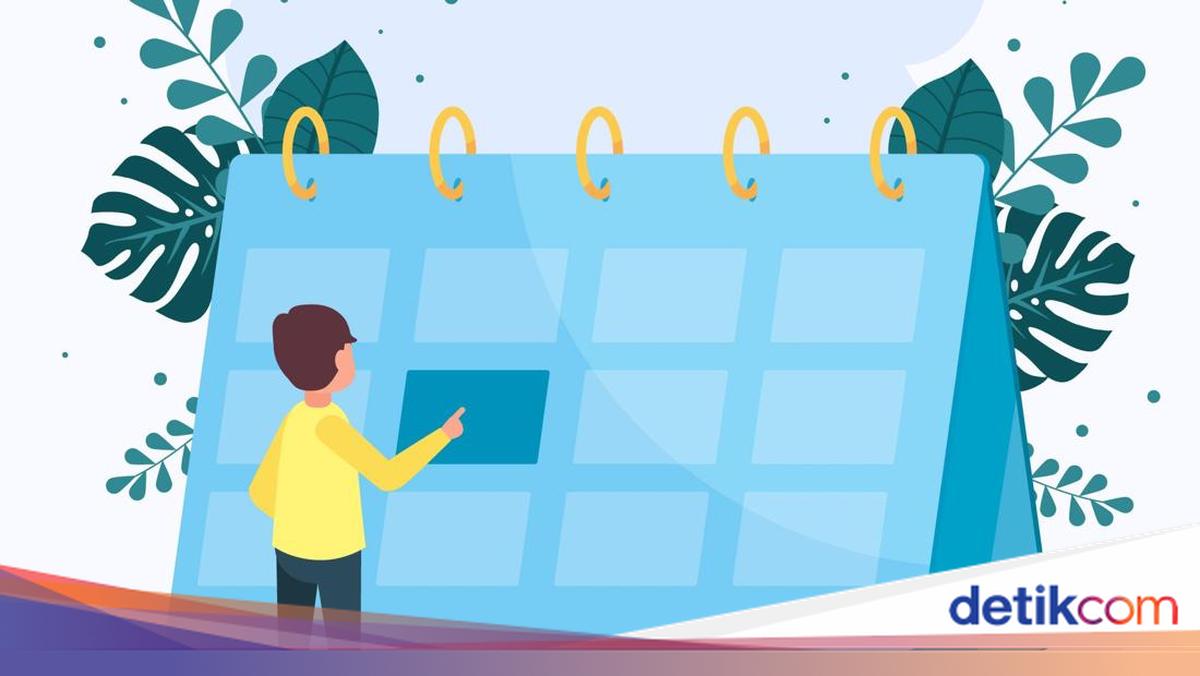Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Dunia bisnis global kini terjebak dalam jaring yang rumit--jerat geopolitik yang semakin mengencang. Di satu sisi, inovasi teknologi membuka peluang tak terbatas. Di sisi lain, rivalitas antar-negara adidaya telah mengubah pasar menjadi medan pertarungan baru.
Dunia telah memasuki era nasionalisme teknologi (techno-nationalism) di mana inovasi tidak lagi sekadar alat kemajuan, melainkan senjata untuk ekspansi ekonomi dan kontrol ideologis.
Pertarungan sesungguhnya kini tidak lagi hanya terjadi di etalase toko atau aplikasi daring. Medan perang yang sesungguhnya adalah ruang rapat badan standardisasi dan lembaga regulasi internasional. Di sanalah negara-negara kuat dan korporasi raksasa berebut pengaruh untuk mengendalikan aturan main yang akan menentukan siapa pemenang dan siapa yang kalah di pasar.
Persaingan modern berpusat pada kemampuan suatu negara untuk membentuk regulasi dan standar teknis yang menguntungkan kepentingan nasional mereka. Contoh paling nyata adalah pertarungan infrastruktur 5G antara Amerika Serikat (AS) dan China. Ini bukan sekadar memperebutkan pangsa pasar ponsel, tetapi upaya mendominasi infrastruktur digital masa depan.
AS merespons dominasi China dengan melarang perusahaan domestik menggunakan peralatan Huawei dan ZTE dengan alasan keamanan dan ancaman spionase. Sebaliknya, China memperluas pengaruhnya melalui program "Digital Silk Road," menawarkan investasi infrastruktur 5G murah yang terikat pada standar teknis buatan Beijing.
Perusahaan China seperti Huawei, Alibaba, dan ZTE telah mendominasi kontrak infrastruktur digital di Asia Tenggara, dengan investasi yang diperkirakan mencapai lebih dari $17 miliar sejak 2013 dalam proyek smart city, data center, dan jaringan telekomunikasi.
Dominasi ini berakar kuat di forum standardisasi global. Di International Telecommunication Union (ITU), pertarungan sesungguhnya terjadi. Menurut data IPlytics Patent Intelligence (2024), Huawei menguasai sekitar 12%-15% paten esensial 5G global, menjadikannya pemain terdepan dalam teknologi ini.
Dominasi paten ini memaksa pemain kecil membayar lisensi mahal atau tersingkir dari pasar. Pada tahun 2024 saja, pendapatan lisensi teknologi Huawei diperkirakan mencapai ratusan juta dolar AS. Pemain besar lainnya seperti Qualcomm (9%-10%), Samsung, dan Nokia turut menguasai paten strategis ini, menciptakan semacam "gerbang tol ekonomi" bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi dalam ekosistem 5G.
Regulasi Domestik sebagai Senjata Geopolitik
Di luar standar teknis, regulasi domestik berevolusi menjadi senjata geopolitik yang tangguh. Contohnya adalah CHIPS and Science Act 2022 senilai $280 miliar di AS--dengan $52,7 miliar khusus untuk industri semikonduktor.
Regulasi ini bukan sekadar insentif industri biasa, melainkan upaya sistematis untuk memutus ketergantungan pasokan chip kritis dari Taiwan dan China. Subsidi ini disertai syarat ketat: perusahaan penerima dana dilarang memperluas produksi chip canggih di China selama 10 tahun ke depan, secara efektif memaksa reshoring rantai pasokan semikonduktor.
Di Eropa, Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) yang awalnya dirancang untuk melindungi privasi warga telah menjadi penghalang pasar yang efektif. Biaya kepatuhan yang mencapai ratusan ribu hingga jutaan dolar memberatkan perusahaan luar Eropa, terutama startup.
Otoritas Persaingan sebagai Alat Geopolitik
Otoritas persaingan usaha telah berevolusi menjadi pemain kunci dalam konflik geopolitik ini. Perannya kini melampaui sekadar menjaga harga dan mencegah monopoli tradisional. Berdasarkan teori kekuatan struktural (structural power) Susan Strange, negara-negara kuat berlomba menguasai struktur pengetahuan dan produksi, dan otoritas persaingan menjadi alat utama di lapangan.
Di AS, Federal Trade Commission (FTC) dan Departemen Kehakiman (DOJ) kini menyelidiki merger teknologi bukan hanya karena potensi kerugian bagi konsumen, tetapi juga karena "bahaya bagi persaingan masa depan" di sektor strategis seperti AI dan semikonduktor--yang terkait langsung dengan keamanan nasional. Akuisisi yang dulu lolos dengan mudah kini menghadapi pengawasan ketat jika melibatkan teknologi dual-use atau data sensitif.
European Commission pun kerap mengesampingkan prinsip persaingan demi kepentingan geopolitik. Contoh nyata adalah Temporary Crisis Framework (Maret 2022) yang melonggarkan aturan persaingan sebagai respons invasi Rusia ke Ukraina.
Pada Juli 2022, framework ini bahkan diamendemen untuk mendukung rencana REPowerEU dalam mengurangi ketergantungan Uni Eropa pada bahan bakar fosil Rusia. Langkah ini membuktikan bahwa ketika menghadapi krisis geopolitik, European Commission rela mengesampingkan prinsip persaingan murni demi kepentingan strategis Uni Eropa secara keseluruhan.
Setali tiga uang, China pun sama saja. State Administration for Market Regulation (SAMR) bisa tegas dengan menjatuhkan denda 18,2 miliar yuan (sekitar $2,8 miliar) terhadap Alibaba pada April 2021 atas tuduhan penyalahgunaan posisi dominan, namun cenderung lunak pada perusahaan milik negara yang merger untuk menciptakan "national champions." Ini membuktikan bahwa otoritas persaingan telah menjadi alat kebijakan industri yang fleksibel sesuai kepentingan nasional.
Strategi Bertahan di Tengah Jerat yang Mengencang
Di tengah jerat geopolitik yang semakin mengencang, bisnis yang mampu bertahan adalah yang pandai menavigasi celah-celah fragmentasi global. Setidaknya terdapat tiga strategi utama yang bisa diterapkan.
Pertama, aliansi lintas batas. Strategi ini menjadi kunci untuk mengurangi risiko geopolitik. Contohnya adalah TSMC, raksasa semikonduktor Taiwan. Menghadapi tekanan dari AS dan ancaman dari China, TSMC mendiversifikasi produksi dengan investasi total hingga $65 miliar di Arizona, termasuk pabrik baru di Jepang dan Jerman.
Meskipun proyeksi awal ambisius, strategi diversifikasi geografis ini secara bertahap mengurangi konsentrasi risiko di Taiwan sekaligus memperkuat hubungan dengan mitra strategis seperti Apple dan NVIDIA.
Kedua, desain modular. Pendekatan ini membantu perusahaan menembus pasar yang terpecah tanpa kehilangan skala ekonomi. Industri farmasi memberikan contoh sempurna: perusahaan seperti Novo Nordisk membangun fasilitas manufaktur modular yang dapat disesuaikan dengan regulasi berbeda di setiap negara.
Pada tahun 2024, Novo meluncurkan fasilitas produksi senilai $1,2 miliar di Denmark dengan desain modular yang memungkinkan rekonfigurasi cepat untuk memenuhi standar Good Manufacturing Practice (GMP) yang berbeda antara FDA AS, EMA Eropa, dan regulator Asia.
Pendekatan serupa diterapkan Procter & Gamble yang mengadaptasi formulasi dan packaging produk seperti deterjen untuk pasar berbeda--versi konsentrat tinggi di Eropa sesuai regulasi lingkungan, dan versi standar dengan harga terjangkau di pasar negara berkembang.
Langkah itu dilakukan sambil mempertahankan efisiensi produksi melalui platform manufaktur yang dapat disesuaikan. Meski menambah kompleksitas operasional, strategi ini memungkinkan perusahaan tetap kompetitif di berbagai yurisdiksi regulasi yang semakin terfragmentasi.
Ketiga, memanfaatkan keunggulan lokal. Regulasi domestik bisa menjadi perisai dari serbuan perusahaan global. Menurut teori liability of foreignness, perusahaan asing selalu membayar "biaya keasingan" untuk memahami pasar lokal--mulai dari memahami preferensi konsumen hingga menavigasi birokrasi dan jaringan bisnis setempat.
Sementara itu, perusahaan lokal bisa memanfaatkan celah di sistem hukum atau infrastruktur (konsep institutional voids) untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru. Gojek dan Grab, misalnya, berhasil mendominasi Asia Tenggara bukan karena teknologi superior, tetapi karena pemahaman mendalam tentang kebutuhan pasar lokal dan kemampuan beradaptasi dengan infrastruktur pembayaran serta regulasi transportasi yang berbeda di setiap negara.
Masa Depan Milik yang Paling Adaptif
Jelaslah, di tengah rivalitas AS-China yang semakin panas, masa depan milik mereka yang paling pintar mengubah fragmentasi menjadi keuntungan. Kuncinya adalah menggabungkan kecerdasan lokal dengan visi global: membangun aliansi netral, merancang produk adaptif, dan memperkuat posisi di meja perundingan internasional.
Sebagaimana disampaikan pakar geopolitik Parag Khanna dalam berbagai analisisnya, abad ke-21 akan dikuasai oleh negara dan korporasi yang mampu mengendalikan kerangka regulasi, bukan hanya teknologi semata.
Persaingan bisnis global kini bukan lagi cuma soal produk atau harga, tetapi tentang siapa yang mampu membentuk aturan mainnya. Di tengah jerat geopolitik yang mengencang, hanya yang paling adaptif yang akan bertahan dan berkembang.
(miq/miq)