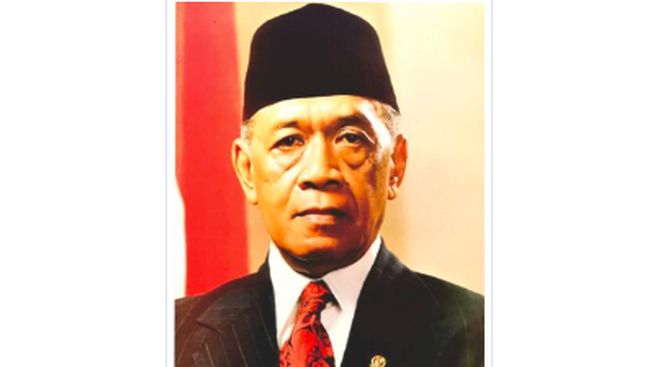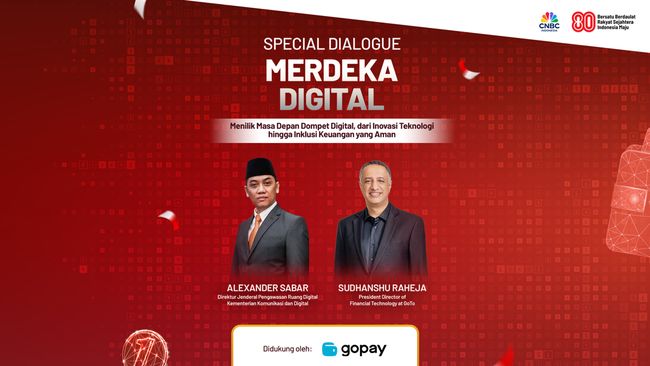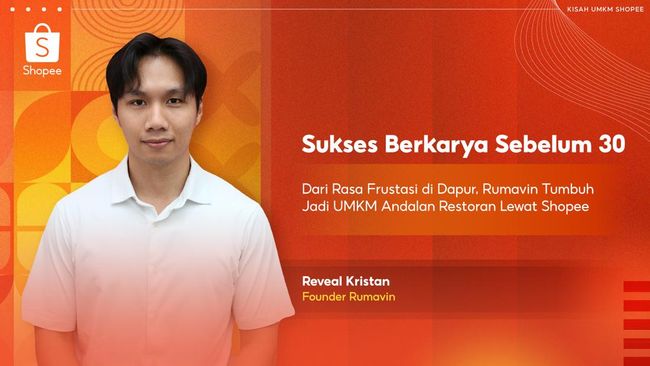Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Bayangkan Ratri, seorang lulusan politeknik di Kendal, Jawa Tengah, yang dua tahun lalu merakit mesin diesel, kini berdiri di lini perakitan panel surya. Upahnya naik, keterampilannya bertambah, dan ia merasa ikut menulis babak baru transisi energi Indonesia.
Kisah Ratri bukan anomali. Ia cerminan gelombang green jobs yang perlahan menepi di ribuan kecamatan, digerakkan oleh lonjakan investasi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034.
RUPTL edisi terbaru menandai pergeseran strategi pembiayaan infrastruktur listrik kita: dari dominasi proyek berbasis batu bara ke portofolio hijau yang terukur. Total kebutuhan investasi sepuluh tahun ke depan dipatok US$ 188 miliar atau sekitar Rp 2.967 triliun, setara 13 % Produk Domestik Bruto (PDB) kita hari ini. Angka ini mencakup belanja proyek Rp 2.699 triliun dan maintenance capex plus bunga konstruksi Rp 268 triliun, tersebar merata antara PLN dan pelaku swasta.
Lebih dari dua pertiga dana tersebut mengalir ke sektor pembangkitan. Dari total Rp 2.134 triliun belanja pembangkit, 71 % disediakan model independent power producer (IPP) sehingga perbankan domestik, dana pensiun, dan dana syariah punya ruang besar menyerap obligasi hijau PLN dan sukuk pemerintah berikutnya. Skema blended finance-memadukan sovereign green sukuk, Just Energy Transition Partnership, dan dana transisi ADB, akan menjadi sabuk pengaman fiskal agar APBN tidak terbebani.
Mengapa hijau? Karena penambahan kapasitas listrik selama periode ini mencapai 69,5 GW, dan 76 % di antaranya berasal dari EBT plus storage 10,3 GW. Kapasitas surya dan bayu saja melonjak dua kali lipat menjadi 24,3 GW, sedangkan nuklir dipasang simbolis 0,5 GW sebagai jembatan teknologi rendah karbon jangka panjang. Hasilnya, bauran EBT diproyeksikan naik 2,5 kali menjadi 34,3 % pada 2034, lebih cepat daripada target Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.
Di balik megawatt, ada manusia. Eksekusi RUPTL diprediksi menyerap 1,7 juta tenaga kerja di seluruh rantai nilai ketenagalistrikan, dari manufaktur panel, konstruksi jaringan transmisi, hingga pemeliharaan gardu distribusi. Dua klaster terbesarnya: 836.696 pekerja di sektor pembangkit dan 881.132 di jaringan. Yang menggembirakan, 91% porsi pembangkit, lebih dari 760 ribu orang tergolong green jobs karena berhubungan langsung dengan EBT.
Klasifikasi detailnya menunjukkan peluang reskilling masif: proyek PLTS membutuhkan 348.057 teknisi, PLTA/mini-hydro 94.195, pumped-storage 68.193, solusi baterai 68 ribuan, hingga tenaga kerja spesifik nuklir 129.759 yang memerlukan disiplin keselamatan tinggi. Angka-angka ini memberi peta jalan kurikulum baru bagi SMK energi, politeknik teknik listrik, hingga program sarjana terapan mekatronika.
Dampak ekonomi tidak berhenti di penciptaan kerja. Kajian internal PLN memperkirakan belanja Rp 300 triliun per tahun itu akan menambah rata-rata 1,4 % PDB tahunan-pendorong penting menuju sasaran pertumbuhan ekonomi nasional 8% pada 2029. Artinya, setiap rupiah obligasi hijau yang berhasil diterbitkan bukan hanya memotong emisi, tapi turut mempertebal dompet negara dan kantong rumah tangga via efek multiplier.
Namun uang besar tidak otomatis bermuara pada kesejahteraan jika ekosistem keuangan dan ketenagakerjaan belum siap. Laporan RUPTL memetakan kebutuhan investasi rata-rata Rp 278 triliun per tahun; 56 % di antaranya harus dipenuhi swasta melalui IPP, green bond, atau venture capital industri storage.
Pada saat yang sama, sektor keuangan nasional baru menyalurkan kredit hijau sekitar 6 % dari total portofolionya. Tanpa taksonomi hijau yang tegas dan insentif fiskal-misalnya pemotongan pajak bagi bunga pinjaman EBT, bank dalam negeri akan kalah cepat dari lembaga multilateral berbunga rendah.
Tantangan serupa hadir di pasar kerja. Dari 1,7 juta posisi yang disiapkan, kurang dari separuh dapat diisi oleh lulusan program vokasi energi terbarukan saat ini. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan kapasitas pelatihan balai latihan kerja untuk teknologi panel surya hanya 15 ribu orang per tahun; butuh loncatan sepuluh kali lipat agar tidak terjadi job-mismatch ketika proyek utility-scale PLTS di Kalimantan masuk fase konstruksi.
Pemerintah bisa meniru model micro-credential cepat-kursus 6-12 minggu bersertifikasi. Asalkan dibiayai Dana Perwalian Transisi Energi dan dikalibrasi dengan rencana proyek tiap provinsi.
Apa resepnya agar pembiayaan hijau sungguh-sungguh menetas menjadi pekerjaan hijau?
Pertama, mewajibkan setiap transaksi green bond nasional menyisihkan porsi minimal 2% sebagai Green Workforce Fund. Dana ini dapat membiayai beasiswa, peralatan lab surya-bayu, dan program magang di IPP EBT.
Kedua, mempercepat harmonisasi Sustainable Finance Taxonomy OJK dengan ASEAN Green Taxonomy agar proyek beremisi sedang seperti gas peaker plus carbon capture-tidak menahan arus modal hijau murni.
Ketiga, menyusun Green Jobs Index lintas kementerian sebagai indikator kinerja utama realisasi RUPTL; jika target serapan tenaga kerja tersendat, kementerian teknis wajib merevisi stimulus fiskal dan TKDN.
Keempat, menggabungkan kebijakan hilirisasi nikel, bauksit, dan silika dengan rencana industri panel surya domestik. Setiap gigawatt PLTS butuh ±6 000 ton kaca kaca low-iron, 13 000 ton aluminium frame, dan ribuan sel surya; rantai pasok ini membuka ruang re-shoring manufaktur sekaligus memperluas kebijakan harga gas industri tertentu.
Kelima, memprioritaskan proyek Listrik Desa (Lisdes) beranggaran Rp 42,3 triliun hingga 2029 karena 10.068 dusun penerima akan menjadi laboratory transisi energi mikrogrid, lengkap dengan 394 MW kapasitas PLTS perdesaan. Setiap instalasi desa mencetak operator lokal, menjaga agar manfaat investor tidak hanya mampir di kota besar.
Distribusi manfaat inilah yang kelak menentukan legitimasi transisi. Kalimantan Timur-yang bersiap menjadi ibu kota baru-membutuhkan 7 % tenaga kerja RUPTL; Sulawesi, dengan rencana PLTA dan pumped-storage besar, menampung 11 %.
Tanpa pipeline pelatihan terarah, provinsi pengirim tenaga kerja seperti NTT atau Papua berisiko hanya menjadi pemasok buruh terampil migran, bukan pusat industri hijau itu sendiri. Di sinilah pemerintah daerah bisa berperan: merealokasi Dana Bagi Hasil EBT menjadi beasiswa politeknik energi, memfasilitasi lahan kawasan industri hijau, dan memadukan sertifikasi nasional dengan standar International Renewable Energy Agency (IRENA).
Akhirnya, transisi energi bukanlah bentang kabel tegangan tinggi atau modul surya di hamparan tandus belaka. Ia adalah orkestrasi modal finansial dan modal manusia, di mana lembar obligasi hijau di Jakarta harus beresonansi sampai kursi operator turbin di Mamuju.
Ketika pembiayaan hijau disangga regulasi cerdas dan kurikulum adaptif, kisah Ratri tak akan menjadi pengecualian; ia akan menjelma jadi statistik baru ekonomi hijau-sebuah garis tren yang memastikan janji net zero emission 2060 bukan sekadar deklarasi di podium, melainkan mata pencarian nyata bagi jutaan warga.
Jika kita gagal menautkan rupiah hijau dengan helm kuning di lapangan, RUPTL hanya akan tercatat sebagai "proyek kertas" paling ambisius dekade ini. Tetapi jika kita berhasil, setiap kilowatt bersih yang menyala akan dilatari senyum pekerja baru, bukti bahwa investasi hijau memang bisa-dan harus-bertumbuh bersama pekerjaan hijau.
(miq/miq)